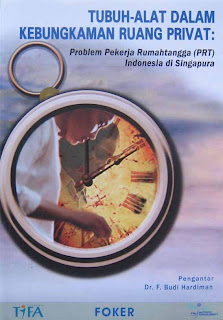 F. Budi Hardiman
F. Budi Hardiman
Tubuh-Alat dalam Kebungkaman Ruang Privat: Tentang PRT Indonesia di Singapura, 2006
Globalisasi dan Depersonalisasi
SALAH satu fenomen mencolok dalam era globalisasi ini, menurut Richard Sennett, adalah perubahan yang sangat cepat dalam penghayatan ‘kerja’ dan ‘tempat’. Pertama, pekerjaan kontrakan dalam waktu pendek mengganti karier yang mapan. Jika dulu kelas buruh merasakan ketakpastian masa depan dan kecemasan, dalam era pekerjaan kontrakan ini kelas menengah juga mengalaminya. Kedua, karena ekonomi pasar menembus sekat-sekat negara nasional, birokrasi-birokrasi, pemerintahan-pemerintahan dan perusahaan-perusahaan gigantis menjadi lebih fleksibel. Namun justru fleksibilitas itulah yang menyebabkan mereka menjadi institusi-institusi yang tidak pasti. Proses ini mengubah makna ‘tempat’ secara drastis: Kurang dari lima dasawarsa yang lalu orang masih percaya bahwa suatu ‘bangsa’ dapat menentukan nasibnya sendiri, karena bangsa memukimi suatu ‘tempat’ yang pasti; tetapi dalam era jejaring ekonomi yang mengaburkan batas-batas geopolitis ini, politik, yakni self-determination itu, terpaksa bisa ditawar-tawar oleh kepentingan-kepentingan pasar.
Lihat
resensi
oleh
* Nur Ahmad dalam Rahima
*Rohman Satriani Muhammad,
dalam harian Pikiran Rakyat, 30 Oktober 2006
Terjadi paradoks di sini: Sementara ekspansi pasar telah mencerabut individu dari ‘tempat’ aslinya dan meluncurkannya dalam mekanisme pertukaran bebas dalam pasar global, individu yang tercerabut itu berupaya meraih kembali identitas kolektifnya dari kultur tempat asalnya. Bangsa tuan rumah di tempat asing itupun melihat mereka sebagai organ asing dalam tubuh bangsanya. Karena itu tidaklah mengherankan bahwa kosmopolitanisme (ekonomis) dalam era globalisasi pasar ini berjalan beriring dengan kebencian dan pelecehan terhadap orang-orang asing. Kelas pekerja yang dalam sistem kapitalisme liberal berhadapan dengan pemilik modal dalam negeri yang relatif masih dapat dikenali sebagai person, insitusi atau perusahaan, dalam sistem kapitalisme lanjut (Spaetkapitalismus) dewasa ini berhadapan dengan jejaring modal yang makin impersonal dan abstrak. Dalam kedua era itu, nasib mereka tetap sama: didepersonalisasikan sebagai alat produksi.
Dewasa ini, manakala demokrasi dan negara hukum menjadi tuntutan di mana-mana di samping liberalisasi pasar, makin jelaslah bahwa depersonalisasi tidak semata-mata disebabkan oleh eksploitasi ekonomis, melainkan juga oleh lemahnya perlindungan hukum. Dan bila kondisi ini menyangkut “warganegara” yang bekerja di luar negeri, persoalan terletak pada perangkat hukum negara itu. Problem buruh migran seperti yang dialami para Indonesia yang bekerja di sektor domestik di Singapura merupakan salah satu contoh mencolok tentang bagaimana depersonalisasi berkaitan dengan apa yang saya sebut di sini ‘keterlantaran legal’, yakni suatu keadaan di mana seorang individu dilupakan sebagai manusia karena hak-haknya tidak dilindungi, sehingga tubuhnya didegradasikan ke status alat kerja (bukankah sejak dini di PJTKI, PRT ditangani sebagai ‘profit machine’ yang lebih dilihat kuantitas kemampuan kerjanya daripada kualitasnya sebagai person?). Eksploitasi atas tubuh orang lain sebagai alat kerja dapat dibatasi dengan hukum, yakni dalam arti spesifik: perlindungan hak. Yang sebaliknya juga benar: Keterlantaran legal mendegradasikan tubuh pekerja ke status alat-alat. Di sini “kerja” dan “tempat” memainkan peranan penting, karena “hak” meletakkan seorang manusia pada suatu “tempat” yang tidak boleh dimasuki orang lain tanpa izinnya.
Keterlantaran Legal
Berdasarkan laporan the Institute for Ecosoc Rights (IER) tentang “Pekerja Rumahtangga (PRT) Indonesia di Singapura” , keterlantaran legal itu memberi kontribusi yang besar terhadap perlakuan kurang manusiawi yang diderita oleh para PRT migran Indonesia. Marilah kita melihat bagaimana keterlantaran legal mengubah tubuh manusia menjadi tubuh-alat. Untuk ‘dapat diterlantarkan secara legal’ diperlukan suatu pra-kondisi yang membuat mereka tampak ‘berlebihan’ untuk mendapatkan ‘hak’ mereka: Pertama, kebanyakan mereka berasal dari kelas-kelas bawah masyarakat dan wilayah-wilayah miskin; kedua, kebanyakan mereka adalah perempuan; ketiga, kebanyakan mereka tidak memiliki keahlian teknis untuk bekerja dan ketrampilan praktis yang memadai untuk berkomunikasi dalam bahasa tuan rumah; keempat, tidak semua mengerti isi kontrak kerja yang mereka tandatangani; kelima, mereka semua bukanlah ‘warganegara’ tempat mereka bekerja; dan yang keenam dan terpenting adalah bahwa mereka bekerja di dalam ruang privat, rumah, yang sejak zaman kuno tidak boleh ditembus oleh sorot mata publik, karena berada dalam wilayah kekuasaan kepala keluarga. Mereka memiliki tubuh. Dan tubuh inipun tampaknya tidak dapat dijadikan bahan negosiasi untuk mendapatkan hak mereka. Misalnya, tubuhnya sakit dan lelah, namun harus tetap bekerja.
Kondisi pertama sampai keempat tidak khas dihadapi PRT Migran, karena hal serupa juga dihadapi PRT dalam negeri. Posisi tawar yang rendah berkorelasi dengan sikap merendahkan dan eksploitatif. Itu juga terjadi di Jakarta dan kota-kota besar Indonesia. Problem khas yang dihadapi PRT migran adalah kondisi kelima, yakni bahwa mereka bukan warganegara tempat mereka bekerja dan ditambah kondisi keenam bahwa mereka bekerja ‘dalam ruang privat’. Apa artinya ini? “Orang asing” tidak hanya berada di jalan-jalan kota atau di kantor-kantor, melainkan juga persis “di dalam rumah”, yakni masuk ke dalam ruang privat. Karena ruang privat itu rentan terhadap hubungan dominasi yang imun terhadap intervensi publik, “orang asing” yang bekerja di sini – jika tidak dipersepsi sebagai ‘ancaman’ – dihadapi sebagai objek, yaitu alat kerja. Tentu saja semua orang tahu bahwa hubungan antara tuan rumah dan tamu yang bekerja itu sebatas ‘hubungan fungsional’, namun kebungkaman ruang privat menyembunyikan hal-hal yang lebih daripada sekedar fungsionalisme. Justru “rumah” menyembunyikan tidak hanya intimitas, melainkan juga rasa takut dan kecurigaan, manakala ‘badan asing’ hadir di situ. Tak mengherankan bahwa kamera dibutuhkan untuk memperpanjang mata majikan, sebagaimana halnya cerita tentang peran ‘spion’ yang dilakukan oleh sang nenek dalam laporan IER. Tentu dibutuhkan humanisme universal di dalam soal ini. Namun bukankah sejak awal, saat para PRT ini dilatih di penampungan-penampungan di Indonesia, humanisme itu sudah merupakan kosa kata asing? Bukankah mereka sadar atau tak sadar diperlakukan tanpa hati sebagai angka-angka pendongkrak profit dan devisa?
Dalam ruang publik orang menyerahkan hanya sebagian dari dirinya, yakni perannya sebagai warganegara, namun hubungan dalam ruang privat bisa menghisap seluruh diri, yakni dapat mengontrol bukan hanya tubuh, melainkan juga pikiran dan perasaan. Merefleksikan laporan IER di atas tentang kondisi PRT migran kita di Singapura, cukup mencoloklah proses bagaimana keterlantaran legal membuat para pekerja itu tak hanya tidak lagi menjadi tuan atas tubuh mereka sendiri; ada kasus-kasus di mana identitas kultural mereka juga harus hilang di ‘rumah’ itu (sementara ada kasus-kasus di mana kartu identitas mereka sudah dipalsukan sejak di Indonesia). Sebagai “orang asing”, yakni bukan “warganegara”, mereka tidak dapat mengklaim “hak atas hak” yang melekat pada kewarganegaraan. Maksudnya adalah cara berpikir bahwa seorang manusia baru mendapatkan hak asasinya setelah ia menjadi warganegara. Cara pikir macam ini masih dominan, meski negara-negara beradab di dunia ini sudah mengakui hak-hak asasi universal yang tidak diberikan oleh kewarganegaraan, melainkan semata-mata karena manusia adalah manusia. Hampir seluruh daftar pelanggaran HAM yang dilontarkan IER kepada pemerintah Singapura (seperti: tambahan beban kerja, kekerasan fisik/psikis, pelecehan, diskriminasi, larangan menikah, kebebasan beragama dst.) bermuara pada suatu kondisi bahwa “orang asing” ini bekerja “dalam rumah”, sehingga “logika ruang privat”, yakni despotisme (penaklukan dan cinta), berlaku dalam kebungkaman dan imunitas terhadap yang publik. Laporan IER membongkar kebungkaman itu dan meletakkannya dalam sorotan publik. Ini merupakan suatu langkah penting untuk melindungi hak-hak asasi PRT migran kita.
Himbauan
Bagaimanapun, marilah kita melihat duduk perkaranya secara seimbang dan juga self-reflective. Hakikat setiap transaksi bisnis yang sehat adalah “pertukaran yang fair antara pembeli dan penjual”. Ini juga menyangkut sektor jasa, seperti pekerjaan rumah tangga. Untuk itu berlaku korelasi ini: Semakin tinggi kompetensi pemberi jasa akan semakin tinggi pula posisi tawarnya, dan ini berarti juga semakin tinggi kesadaran akan hak serta tanggungjawabnya. Betul bahwa sejauh menyangkut HAM, tuntutan itu tidak terkait langsung pada kompetensi, sebab perlindungan HAM tak tergantung pada prestasi seseorang, melainkan pada kemanusiaannya. Namun perlu juga disadari bahwa peningkatan kompetensi PRT migran kita akan membantu kita untuk mendesakkan pelaksanaan HAM itu di Singapura, sebab peningkatan kompetensi termasuk peningkatan kesadaran akan hak di pihak PRT migran kita.
Kondisi demografis Indonesia sendiri yang menyediakan massa pengangguran secara berlimpah merupakan kondisi objektif yang kerap menyulitkan peningkatan posisi tawar. Kemiskinan dapat mendegradasikan manusia. Bukan hanya itu, dalam kemiskinan PRT yang sudah disakiti pun akan terus mencari kerja dan bersedia balik demi hidupnya. Kemiskinan membuat mereka tak takut mati dan tak takut nyeri. Namun ketabahan itu tidak dikalkulasi sebagai keutamaan yang direspon dengan respek, melainkan dipandang sebagai kodrat yang sudah melekat pada tubuh-alat sebagai komoditas pasar tenaga kerja. Senang atau tak senang, hukum ekonomi sebagaimana diamati oleh F. Engels dalam laporannya tentang “Kondisi Kelas Pekerja di Inggris” (1845) berlaku, yakni: “Persis sama seperti komoditas, jika jumlahnya terlalu sedikit, harganya naik, yaitu upahnya lebih baik…jika yang ada terlalu banyak, jatuh juga harganya…” Artinya apa? Jika kita mau meningkatkan posisi tawar, sistem seleksi dan pelatihan harus ketat. Namun masalahnya adalah bahwa melemahnya sistem seleksi dan pelatihan berkorelasi dengan melimpahnya para pengangguran di negeri kita dan desakan survival yang juga dihadapi perusahaan penyalur tenaga PRT di tengah-tengah logika kapitalistis untuk maksimalisasi keuntungan. Jika kita merekomendasikan suatu pengetatan sistem kontrol dari pemerintah kita sendiri, suatu pertanyaan balik akan dilontarkan: Apakah suatu instansi yang lemah secara moral dapat secara efektif melakukan kontrol moral dan hukum? Agar pertanyaan serupa tidak bergulir seperti lingkaran setan, suatu kepercayaan terhadap para aktor civil society baik yang bekerja di Indonesia maupun di Singapura harus ada. Kontrol itu harus dilakukan bersama dalam sebuah sistem yang disepakati dan dilaksanakan secara konsisten.
Bagaimanapun, penelitian-penelitian seperti yang dilakukan IER harus dimultiplikasi untuk memberi suara kepada korban dalam kebungkaman ruang privat di manapun (mungkin baik melebarkan riset serupa dengan responden para PRT yang bekerja di dalam metropolis Jakarta, karena bisa jadi kondisi mereka di dalam ‘rumah bangsa sendiri’ tidak lebih baik daripada yang ditemukan di Singapura). Pesan tegas dari penelitian ini adalah: Jangan terpukau pada sukses-sukses kualitatif yang dihitung dengan angka-angka, sebab angka-angka itu menyangkut person-person yang berperasaan dan mudah terluka. Kasus-kasus bunuh diri PRT migran kita di Singapura hanyalah puncak gunung es masalah kualitatif yang lebih besar, yakni: kemanusiaan yang terancam oleh gilasan mekanisme pasar tenaga kerja pada ranah global, komodifikasi tubuh manusia sebagai alat kerja. Tubuh-alat yang berhadapan langsung dengan hal yang dirty (kotor), dangerous (berbahaya) dan demeaning (hina) inilah yang menumbuhkan kesadaran pemberi pekerjaan sebagai “bangsa tuan”. Penistaan ini tak semata-mata kesalahan tuan rumah, melainkan juga terletak pada cara bagaimana tamunya menghargai dirinya sendiri. Dan sejauh ini menyangkut “rumah kita”, kita tak akan melepaskan warganegara kita tanpa kompetensi-kompetensi, hak-hak dan jaminan-jaminan yang meningkatkan harga diri mereka sebagai manusia. Kesetaraan diraih hanya jika mereka mampu menegaskan diri dengan kompetensi dan haknya di hadapan pemberi kerja.**




















Untuk Hari Ini
Babu Negara
Olkes Dadilado
Education21
Rairo
Geworfenheit
Kodrat Bergerak
Chi Yin
aha!
John's blog
ambar
andreas harsono
bibip
Space & (Indonesian) Society
dreamy gamer
sundayz
wadehel
rudy rushady
Timor Merdeka
G M
Karena Setiap Kata adalah Doa
Sarapan Ekonomi
wisat
Adhi-RACA